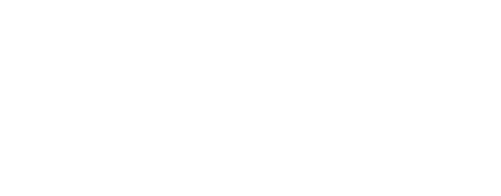RATUSAN orang berdesakan antre di pintu pemberangkatan KAI CommuterLine Stasiun Tugu Yogyakarta, Sabtu 7 Desember 2024. Jarum jam menunjukkan pukul 08.40. Rencananya Kereta Rel Listrik (KRL) rute Yogyakarta menuju Palur diberangkatkan pukul 08.50.
Dari pengeras suara terdengar pengumuman agar para pelanggan KRL di peron pemberangkatan CommuterLine bergeser ke arah barat. Dalam hitungan detik, ratusan calon penumpang bergerak menuju pintu yang belum dibuka dan dijaga beberapa petugas.
Setelah pintu dibuka, orang-orang berusaha saling mendahului untuk berebut mendapatkan tempat duduk. Mereka dengan kekuatannya melepaskan kerumunan dan berlari memilih gerbong yang masih tersedia kursi kosong.
Kupandangi calon penumpang KRL yang berebut ingin mendapatkan kursi. Sampai di antara mereka yang tidak peduli dengan anak-anak, orangtua lanjut usia, dan kaum disabilitas. Telinganya tidak mendengar isak tangis anak yang terlepas dari genggaman orangtua, matanya tidak melihat orangtua lanjut usia yang berjalan memakai tongkat, dan hatinya tidak bisa merasakan orang tunanetra yang meraba-raba mencari pintu masuk gerbong kereta.
Hatiku tergetar ketika mata melihat seorang petugas keamanan KRL berlari menghampiri seorang gadis tunanetra. Dia menuntun gadis itu dan mencarikan tempat duduk yang diprioritaskannya bagi penyandang disabilitas. Setidaknya ada empat golongan yang memperoleh tempat duduk prioritas dari pengelola KRL, yakni golongan lanjut usia, wanita hamil, ibu membawa anak, dan penyandang disabilitas.
Gadis tunanetra itu dicarikan tempat duduk bersebelahan denganku. Kebetulan penulis juga masuk dalam golongan lanjut usia. Perempuan tunanetra itu membawa bungkusan kotak dan tongkat lipat. Setelah duduk, dia asyik menggunakan telepon genggamnya. Gadis itu meraba-raba layar gadget, lalu mendengarkan suara dari handphone-nya.
“Gimana cara memakai handphone-nya mbak? Kalau mau mengirimkan pesan caranya bagaimana,” tanyaku, mengawali perbincangan dengan gadis tunanetra di dalam gerbong KRL Jogja-Solo, Sabtu 7 Desember 2024. Sebelum bertanya, aku melihat di layar handphone-nya tidak terlihat huruf-huruf seperti handphone kebanyakan.
“Kami pakai voicenote pak. Kalau mau chat, kita raba layar nanti terdengar suara bunyi huruf ,” kata gadis itu menjelaskan. Jadi seperti braile phone dan alat komunikasi seperti itu sudah familiar di kalangan kaum tunanetra.
Setelah ngobrol sejenak, identitas diri perempuan tunanetra itu mulai sedikit terkuak. Dia bernama Sulastri, tempat tinggalnya di Bolopleret, Juwiring, Klaten, Jawa Tengah. Lastri, panggilan akrabnya, menceritakan kebutaannya bukan dari kecil.
“Saya total tidak bisa melihat itu sejak enam tahun lalu pak,” ungkap Lastri dengan tenang. Sebelumnya sejak kecil, dia bisa melihat dan ketika remaja bekerja di tempat laundry atau jasa cuci dan seterika baju di Juwiring Klaten.
Enam tahun lalu atau sekitar tahun 2018, mata Sulastri terserang glukoma. Mungkin karena tempat tinggalnya di desa, akses rumahsakit sulit terjangkau, pengobatan kurang baik, atau faktor lain, yang menyebabkan penyakit matanya kurang tertangani dengan baik. Sehingga sekarang Lastri menyandang disabilitas tunanetra.
Bagi orang kebanyakan, sulit untuk menerima keadaan yang semula matanya sehat, kemudian tidak bisa berfungsi untuk melihat. Tapi Sulastri terbilang cepat move on. “Kata temen-teman, saya cepat move on,” ungkap Lastri.
Dalam perbincangan di dalam gerbong KRL, Lastri penyandang disabilitas tunanetra ini merasa bahwa tunanetra di Indonesia masih diposisikan sebagai kaum yang dikasihani. “Padahal kami berharap bukan dikasihani, tetapi dihargai sesuai dengan kemampuan kami,” tegasnya.
Selain itu, instansi, lembaga, organisasi, atau perusahaan masih memandang sebelah mata keberadaan kaum disabilitas, khususnya para tunanetra. Misalnya, dalam perekrutan tenaga kerja baru, porsi penerimaan kaum disabilitas sangat kecil. Bahkan beberapa perusahaan tidak menerima kaum disabilitas, karena dianggap tidak produktif.
Lastri menjelaskan, sebenarnya kaum disabilitas itu memiliki keunggulan dibandingkan masyarakat biasa. Keunggulan itu, antara lain konsistensi, ketelitian, dan ketekunan, serta loyal terhadap tempatnya bekerja.

Tidak terasa perjalanan dengan KRL dari Stasiun Tugu Yogyakarta menuju Palur Surakarta sudah melewati sembilan stasiun, yakni Stasiun Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Brosot, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwasari, dan Balapan Solo. Saya mau turun di Stasiun Balapan. Sedangkan Sulastri, penyandang disabilitas tunanetra akan turun di Stasiun Jebres.
“Pelanggan kereta api Indonesia yang terhormat, sebentar lagi kita akan sampai di Stasiun Balapan. Bagi yang akan turun di Stasiun Balapan harap mempersiapkan diri. Jangan lupa tas dan barang bawaannya. Pintu sebelah kiri akan dibuka,” kata petugas KAI menyampaikan informasi kepada penumpang KRL.
Perbincanganku yang mengesankan dengan gadis tunanetra terhenti di Stasiun Balapan Solo. Namun ungkapan yang ditegaskan “Kami tidak perlu dikasihani, tetapi kami ingin dihargai” terus terngiang mengiringi langkah kakiku menuju pintu keluar Stasiun Balapan Solo. (Ono)
Artikel Bersama Gadis Tunanetra di Dalam Gerbong KRL Jogja-Solo pertama kali tampil pada Wiradesa.co.